[Tabik] Sebuah Obituari untuk Rachel Corrie by Goenawan Mohamad

Rachel Corrie yang ada di surga, selalu kembalilah namamu. Semoga selalu kembalilah ingatan kepada seseorang yang bersedia mati untuk orang lain dalam umur 23 tahun, seseorang yang memang kemudian terbunuh, seakan-akan siap diabaikan di satu Ahad yang telah terbiasa dengan kematian.
Hari itu 16 Maret yang tak tercatat, karena hari selalu tak tercatat dalam kehidupan orang Palestina, orang-orang yang tahu benar, dengan ujung saraf di tungkai kaki mereka, apa artinya ”sementara”. Juga di Kota Rafah itu, di dekat perbatasan Mesir, tempat hidup 140 ribu penghuni—yang 60 persennya pengungsi—juga pengungsi yang terusir berulang kali dari tempat ke tempat. Pekan itu tentara Israel datang, seperti pekan lalu, ketika 150 laki-laki dikumpulkan dan dikurung di sebuah tempat di luar permukiman. Tembakan dilepaskan di atas kepala mereka, sementara tank dan buldoser menghancurkan 25 rumah kaca yang telah mereka olah bertahun-tahun dan jadi sumber penghidupan 300 orang—orang-orang yang sejak dulu tak punya banyak pilihan.
Tentara itu mencari ”teroris”, katanya, dan orang-orang kampung itu mencoba melawan, mungkin untuk melindungi satu-dua gerilyawan, mungkin untuk mempertahankan rumah dan tanah dari mana mereka mustahil pergi, karena tak ada lagi tempat untuk pergi.
Saya bayangkan kini Rachel Corrie di surga, sebab hari itu ia, seorang perempuan muda dari sebuah kota yang tenang di timur laut Amerika Serikat, memilih nasibnya di antara orang-orang di Rafah itu: mereka yang terancam, tergusur, tergusur lagi, dan tenggelam. Hari itu ia melihat sebuah buldoser tentara Israel menderu. Sebuah rumah keluarga Palestina hendak dihancurkan. Dengan serta-merta ia pun berlutut di lumpur. Ia mencoba menghalangi.
Tapi jaket jingga terang yang ia kenakan hari itu tak menyebabkan serdadu di mobil perusak itu memperhatikannya. Prajurit di belakang setir itu juga tak mengacuhkan orang-orang yang berteriak-teriak lewat megafon, mencoba menyetopnya. Buldoser itu terus. Tubuh itu dilindas. Tengkorak itu retak. Saya bayangkan Rachel Corrie di surga setelah itu; ia meninggal di Rumah Sakit Najar.
Rachel yang di surga, selalu kembalilah namamu. Korban dan kematian di hari ini menjadikan kita sebaya rasanya. Kau terbunuh di sebuah masa ketika tragedi dibentuk oleh berita pagi, dan makna kematian disusun oleh liputan yang datang dan pergi dengan sebuah kekuasaan yang bernama CNN. Tahukah kau, di seantero Amerika Serikat, tanah-airmu, tak terdengar gemuruh suara protes yang mengikuti jenazahmu?
Tentu kita maklum, bukan singkat ingatan semata-mata yang menyebabkan sikap acuh tak acuh setelah kematianmu di hari itu. Bayangkanlah betapa akan sengitnya amarah orang dari Seattle sampai dengan Miami, dari Gurun Mojave sampai dengan Bukit Capitol, seandainya kau, seorang warga negara Amerika, tewas di tangan seorang Palestina yang melempar batu.
Tapi kau tewas di bawah buldoser tentara Israel; kau berada di pihak yang keliru, anakku. Itulah memang yang diutarakan beberapa orang di negerimu ketika mereka menulis surat ke The New York Times. Mereka menyalahkanmu. Sebab kau datang, bersama tujuh orang Inggris dan Amerika lain, untuk menjadikan tubuhmu sebuah perisai bagi keluarga-keluarga Palestina yang menghadapi kekuatan besar pasukan Israel di kampung halaman mereka. Kau melindungi teroris, kata mereka. Meskipun sebenarnya kau datang dari Olympia, di dekat Teluk Selatan Negara Bagian Washington, bergabung dengan International Solidarity Movement, untuk mengatakan: ”Ini harus berhenti.”
Kau salah, Rachel, kata mereka. Tapi kenapa? Dalam sepucuk e-mail bertanggal 27 Februari 2003 yang kemudian diterbitkan di surat kabar The Guardian, kau menulis, ”Kusaksikan pembantaian yang tak kunjung putus dan pelan-pelan menghancurkan ini, dan aku benar-benar takut…. Kini kupertanyakan keyakinanku sendiri yang mendasar kepada kebaikan kodrat manusia. Ini harus berhenti.”
Saya bayangkan Rachel di surga, saya bayangkan ia agak sedih. Ia dalam umur yang sebenarnya masih pingin pergi dansa, punya pacar, dan menggambar komik lagi untuk teman-teman sekerjanya. Tapi di sini, di Rafah, ada yang ingin ia stop; bersalahkah dia? Beberapa kalimat dalam surat kepada ibunya menggambarkan perasaannya yang intens: ”Ngeri dan tak percaya, itulah yang kurasakan. Kecewa.”
Ia kecewa melihat ”realitas yang tak bermutu dari dunia kita”. Ia kecewa bahwa dirinya ikut serta di kancah itu. ”Sama sekali bukan ini yang aku minta ketika aku datang ke dunia ini,” tulisnya, ”Bukan ini dunia yang Mama dan Papa inginkan buat diriku ketika kalian memutuskan untuk melahirkanku.”
Apa yang mereka inginkan, Rachel, dan apa yang kau minta? Berangsur-angsur kau pun tahu: kau tak menghendaki sebuah rumah yang begitu nyaman, begitu ”Amerika”, hingga si penghuni tak menyadari sama sekali bahwa ia sebenarnya berpartisipasi dalam sesuatu yang keji, yakni ”dalam pembantaian”. Itulah sebabnya kau berangkat ke Palestina. ”Datang ke sini adalah salah satu hal yang lebih baik yang pernah kulakukan,” begitu kau tulis pada 27 Februari 2003. ”Maka jika aku terdengar seperti gila, atau bila militer Israel meninggalkan kecenderungan rasialisnya untuk tak melukai orang kulit putih, tolong, cantumkanlah alasan itu tepat pada kenyataan bahwa aku berada di tengah pembantaian yang aku juga dukung secara tak langsung, dan yang pemerintahku sangat ikut bertanggung jawab.”
Ia menuduh dirinya sendiri ikut bersalah. Tapi ia meletakkan kesalahan yang lebih besar pada pemerintahnya. Rasanya ia betul. Saya kira ia bahkan bisa juga menggugat jutaan orang Amerika lain yang senantiasa membenarkan apa yang dilakukan Ariel Sharon—hingga dalam keadaan perang dengan Irak sekalipun, dari Washington DC datang tawaran satu triliun dolar untuk bantuan militer langsung kepada Israel, di celah-celah berita tentang orang Palestina yang ditembak dan dihalau, di antara kabar tentang anak-anak Palestina yang tewas. Bukan main—cuma beberapa hari setelah seorang Amerika tewas ditabrak buldoser di Kota Rafah!
Jika ada kepedihan hati di sana, kau pasti mengetahuinya lebih intim, Rachel. Dari lumpur Kota Rafah itu kau pasti mengerti apa yang jarang dimengerti orang Amerika: kekerasan bisa muncul di puing-puing itu, sebagai bagian dari usaha untuk, seperti kau katakan dalam suratmu, ”melindungi fragmen apa pun yang tersisa”. Segalanya telah direnggutkan. Kau akan bisa menunjukkan bahwa Usamah bin Ladin dan Saddam Hussein, dengan wajah mereka yang setengah gelap, menjadi penting karena mereka bisa bertaut dengan gaung Palestina di mana segalanya telah direnggutkan—sebuah pantulan dari keluh lama yang jadi hitam. Sampai hari ini, yang terdengar sebenarnya adalah sebuah gema dari geram bertahun-tahun yang terkadang kacau, terkadang keras, dan senantiasa kalah.
Senantiasa kalah—di Yerusalem, di Kabul, dan, sebentar lagi, di Bagdad.
Tapi adakah kalah segala-galanya? Tidak, kau pasti akan bilang, semoga tidak. Dalam suratmu bertanggal 28 Februari kau ceritakan kepada ibumu sesuatu yang menyebabkan engkau merasa lebih mantap sedikit, di antara perasaan pahitmu menyaksikan hidup yang dibangun oleh ketidakadilan. Tak semuanya ternyata hanya ngeri, tak percaya, dan kecewa. Di celah-celah luka yang merundung penghuni Palestina yang kau kenal di Rafah, kau dapat menyaksikan sesuatu yang lain dari kepedihan. Kau menemukan sesuatu yang belum pernah kau lihat dalam hidupmu sebelumnya: ”…satu derajat kekuatan dan kemampuan dasar manusia untuk tetap menjadi manusia”. Dan kau punya sepatah kata untuk itu: dignity.
Tapi apa kiranya yang bisa didapat dari dignity, dari harga diri, yang menyebabkan manusia tak melata di atas debu sebelum menggadaikan segala-galanya? Tak banyak, tapi juga sangat banyak.
Seperti Bagdad yang akan jatuh, yang lemah akan tetap roboh. Tapi di depan tubuh yang tergeletak di lumpur, tubuh yang terjerembap dan menuding ketidakadilan, kemenangan sang superkuat sekalipun akan terhenti: ia hanya ibarat sebuah buldoser yang sekadar menghancurkan. Genggaman itu kosong. Penaklukan itu ilusi.
Sebab itu, Rachel yang ada di surga, semoga namamu selalu akan kembali. Kini memang saya bimbang, tapi masih ingin saya percaya bahwa hidup selalu membutuhkan yang lain, sesuatu yang bukan fotokopi diri subyek yang bertakhta. Saya masih ingin percaya bahwa tak mustahil akan ada sebuah ruang di mana yang lemah tak terusir, dan yang lain bisa sewaktu-waktu berteriak ”Stop kau!” dan sebab itu merdeka.
Goenawan Mohamad
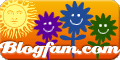
0 comment(s):
Post a comment
<< Home